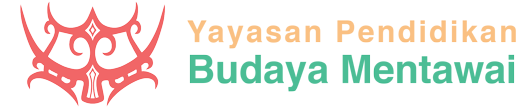“Jurnal ditulis selama ini bicara periode ‘bunga-dihiasi’ pribumi dan waktu yang dihabiskan “pulau kebahagiaan” (Maass, 1902) di ‘pulau kebahagiaan’ (Karny, 1925)”
Mentawai merupakan negara kepulauan yang ditemukan di lepas pantai barat Sumatera (Indonesia) yang terdiri dari sekitar 70 pulau dan pulau. Empat pulau utama adalah Utara dan Pagai Selatan, Sipora, dan Siberut; dengan Siberut – mencakup 4.480 kilometer persegi dan dengan jumlah penduduk sekitar 29.918 [1][1] (Regional Autonomy Website. c.2000.); yang 90% adalah penduduk asli asal Mentawai, yang lain 10% dianggap terdiri dari Minangkabau, Jawa, dan Batak (Bastide, 2008) – menjadi empat dari yang terbesar.
Para nenek moyang orang Mentawai adat diyakini telah bermigrasi pertama ke wilayah tersebut di suatu tempat antara 2000 – 500 SM (Reeves, 2000), sedangkan penjajah pertama dinyatakan, dalam dokumentasi awal oleh John Crisp yang mendarat di pulau-pulau pada tahun 1792, telah tiba pada pertengahan 1700 di perjalanan orang Inggris yang membuat upaya gagal dan untuk mendirikan sebuah pemukiman pertanian lada di sebuah pulau selatan Pagai Selatan (Crisp, 1799). Selama bertahun-tahun sebelum perdagangan ini ada antara masyarakat adat dan daratan Sumatera Cina dan Melayu (Francis, 1839).
Setelah menetapkan kehadiran mereka 40 tahun sebelumnya, sementara penandatanganan kontrol Sumatera dan Semenanjung Malaya, Belanda kembali pada tahun 1864 untuk mengklaim kepulauan Mentawai di bawah kedaulatan Hindia Timur (Mess, 1870); posisi dipertahankan sampai Perang Dunia Kedua. Selama periode ini hubungan antara masyarakat Belanda dan pribumi dilaporkan satu yang memuaskan, seperti yang didokumentasikan melalui akun pembicaraan dengan para tetua Mentawai yang berlabel kali ini sebagai “hari tua yang baik” di mana mereka “menerima harga yang adil dalam perdagangan dan bebas untuk mempraktekkan gaya hidup budaya mereka, Arat Sabulungan” [2][2] Arat Sabulungan adalah eksistensi budaya dimana masyarakat Mentawai adat hidup yang diselenggarakan bersama oleh sebuah sistem kepercayaan yang membayar penghormatan kepada arwah nenek moyang mereka, langit, tanah, laut, sungai, dan segala sesuatu di dalamnya. Dipimpin oleh dukun (Kerei atau Sikerei), upacara ritual cukup umum. (Bakker, 1999).
Selain kampanye militer menegakkan pemberantasan perang suku – perubahan seharusnya disambut oleh Islanders – catatan menunjukkan bahwa Belanda tidak berusaha ikut campur dengan kehidupan sehari-hari orang Mentawai. Jurnal ditulis selama ini bicara periode ‘bunga-dihiasi’ pribumi dan waktu yang dihabiskan “pulau kebahagiaan” (Maass, 1902) di ‘pulau kebahagiaan’ (Karny, 1925).

Pada tahun 1901, August Lett, misionaris pertama ke Mentawai, tiba di pantai selatan Pagai Utara – membangun pandangan yang bertentangan dengan yang ada pada wisatawan awal abad 20 Belanda dan lainnya. Lett, dan misionaris selanjutnya dikirim ke pulau-pulau, ditolak dan dipandang rendah masyarakat adat karena keyakinan mereka takhayul, ritual, dan perilaku budaya; menggambarkan orang-orang sebagai “malas, terbelakang dan bodoh” dan memiliki “penderitaan orang miskin terjebak dalam teror kejahatan” (Hammons, 2010). Pada 1915, setelah beberapa kesulitan – termasuk kematian Agustus Lett (Persoon, 1987) – misionaris telah memperoleh mengkonversi pertama mereka, diperpanjang upaya mereka untuk Sipora dan Siberut dan, pada 1932, telah pergi untuk mendirikan stasiun misi di Maeleppet (Siberut ), (Sihombing, 1979).
“Pada awal 1954, di bawah tujuan Indonesia persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional mulai memperkenalkan pengembangan dan peradaban program yang dirancang untuk ‘mengintegrasikan kelompok suku ke dalam arus sosial utama dan budaya dari negara’ (Persoon 2004)”
Dari sekian banyak perubahan yang dialami oleh orang-orang dari Siberut selama periode ini dan dekade berikutnya – terutama pembentukan koloni pemaksaan di Muara Siberut dan kedatangan dan aturan kekerasan otoritas Jepang selama periode Perang Dunia Kedua – yang paling signifikan, dalam hal asimilasi masyarakat Mentawai, tiba pada tahun 1950 (setelah deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945) ketika Mentawai menjadi bagian dari negara Indonesia (Bakker, 1999).
Pada awal tahun 1954, di bawah tujuan Indonesia persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional mulai memperkenalkan program peradaban yang dirancang untuk ‘mengintegrasikan kelompok suku ke dalam arus utama sosial dan budaya dari negara’ (Persoon 2004) pengembangan dan. Ini, untuk asli Mentawai, berarti pemberantasan praktek Arat Sabulungan; penyerahan paksa, pembakaran dan penghancuran harta yang digunakan untuk memfasilitasi perilaku budaya atau ritual; dan mereka Sikerei (dukun) melepas jubah, dipukuli, dan dipaksa menjadi pekerja paksa dan di penjara.
Berdasarkan Pancasila [3][3] Pertama diartikulasikan pada 1 Juni 1945, Soekarno berpendapat bahwa negara Indonesia masa depan harus didasarkan pada Pancasila: nasionalisme Indonesia; internasionalisme, atau humanisme; persetujuan, atau demokrasi; kesejahteraan sosial; dan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konstitusi Republik Indonesia diundangkan pada tahun 1945, Pancasila telah dicatatkan pada urutan sedikit berbeda dan dalam kata-kata yang berbeda: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi di bawah bimbingan bijaksana konsultasi perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Britannica, dilihat 2012), lima prinsip filsafat negara Indonesia yang dirumuskan oleh pemimpin nasionalis Sukarno Indonesia, Pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan nasional agama baru mereka; mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menjadi milik salah satu dari lima agama yang diakui [4][4] Berdasarkan ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ gagasan Indonesia, terdapat resmi hanya lima agama yang diakui: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha (Tropenbos International 2004: Posisi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Tropis). . Yang, untuk Kepulauan Mentawai, mengakibatkan masuknya segera misionaris dan peningkatan kekerasan dan tekanan pada orang-orang untuk mengadopsi perubahan [5][5] Pada akhirnya banyak yang memilih agama Kristen, karena pandangan yang fleksibel terhadap kepemilikan dan konsumsi babi yang memainkan peran integral dalam sejarah dan budaya Mentawai..

Pada inti dari strategi implementasi program adalah pengembangan dari serangkaian pemukiman kembali (PKMT[6][6] Sebuah singkatan untuk ‘Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat terasing’: Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang terisolasi.) villages (1971); desa (1971); dimana rumah dibangun sesuai dengan desain seragam di daerah dikategorikan samping sungai utama/pantai dan orang-orang dipaksa untuk meninggalkan Uma mereka [7][7] The Uma adalah hub pusat untuk upacara budaya, ritual, dan penyimpanan semua item suci ; itu adalah jenis ‘rumah panjang’ dibangun untuk rumah seluruh klan (delapan atau lebih keluarga inti) pada satu waktu, yang sangat diperlukan pada saat upacara. ‘Uma’ juga merupakan istilah yang digunakan ketika referensi seluruh kelompok. dan tanah leluhur untuk pindah.
Setelah jangka waktu lima tahun pemukiman ini telah dihapus dari status proyek dan di tangan kiri PNS dan pejabat pemerintah setempat untuk mempertahankan kemajuan dan kontrol. Ini juga merupakan waktu di mana perusahaan penebangan kayu mulai muncul di seluruh Kepulauan Mentawai.

Pada akhir 1980-an, setelah penebangan telah menghancurkan hutan Sipora, Utara dan Pagai Selatan, dan – sebelum ditantang oleh pilihan organisasi internasional [8][8] Pada tahun 1980, WWF (dana satwa liar dunia) menerbitkan sebuah laporan berjudul ‘Saving Siberut’ yang, bersama dengan dukungan dari organisasi lain – terutama UNESCO dan Survival International – dan kepentingan internasional tambahan lainnya, membantu membujuk pemerintah Indonesia untuk membatalkan konsesi penebangan dan menyatakan hutan Siberut cagar biosfer. – juga dalam proses mencapai hal yang sama di Siberut, tekanan Pemerintah tentang pemukiman kembali agak santai (terutama karena aliran pariwisata masyarakat adat menarik). Dengan ini, orang-orang di Mentawai menemukan bahwa mereka sekali lagi bebas untuk berlatih kegiatan budaya asli mereka – di daerah yang jauh dari desa-desa.
Namun, berawal dari trjadinya pemaksaan, dan sampai saat ini, jumlah masyarakat adat yang masih aktif berlatih kebiasaan budaya, ritual dan upacara Arat Sabulungan sudah terbatas dengan populasi yang sangat kecil dari kelompok adat, terutama terletak di sekitar Sarereiket dan Sakuddei daerah di selatan Pulau Siberut.